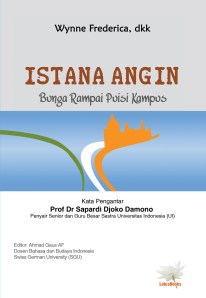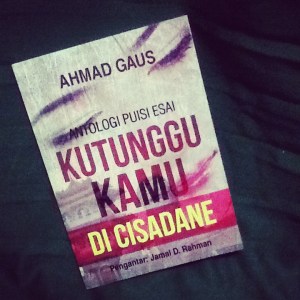Pengantar untuk Buku Puisi Esai:
KUTUNGGU KAMU DI CISADANE
Oleh Ahmad Gaus
Duapuluh tahun kemudian saya kembali menulis puisi. Selama rentang waktu itu saya hanya menulis artikel opini atau kolom di media massa, serta sejumlah buku. Dunia puisi sudah saya tinggalkan, dan nyaris tidak pernah diingat lagi. Saya sudah menganggapnya sebagai masa lalu, catatan kelam dalam karir kepenulisan saya.
Tahun 1991 adalah puncak kebencian saya terhadap puisi—kurun waktu di mana saya banyak menulis dan mengirimkan puisi-puisi saya ke media massa, tapi tidak pernah dimuat. Akhirnya saya muat sendiri dalam majalah mahasiswa yang saya pimpin. Mungkin ini pelajaran penting: seorang penulis tidak perlu bisa menuangkan gagasannya ke dalam semua bentuk tulisan. Saya merasa tidak berbakat menulis karya fiksi seperti puisi dan cerpen (cerita pendek). Ada cerpen yang saya tulis sejak tahun 2007 dan sampai sekarang belum juga selesai. Ada juga puisi yang saya selesaikan selama 3 tahun, padahal puisi itu pendek saja. Mungkin karena saya menuliskannya dengan keraguan yang sempurna—keraguan bahwa saya tidak berbakat menjadi penyair!
Tetapi, saya memang tidak bercita-cita menjadi penyair. Bahkan sampai sekarang. Perkara dulu—saat remaja—saya suka menulis puisi, biasanya karena sedang jatuh cinta. Ada juga puisi-puisi yang saya tulis karena perasaan “dendam” kepada sejumlah penyair yang begitu licik bermain dengan kata-kata. Sejak duduk di bangku Tsanawiyah/SMP saya membaca puisi-puisi karya Amir Hamzah, Chairil Anwar, Goenawan Mohamad, Sapardi Djoko Damono, dan yang lainnya, dengan kekaguman yang meletup-letup. Lalu saya mencoba meniru mereka, menulis puisi. Kemudian saya mengirimkannya ke media massa. Untuk sebagian besar saya tidak tahu nasib puisi-puisi itu, mungkin masuk dalam keranjang sampah. Ada juga redaksi yang berbaik hati mengembalikannya dalam amplop tertutup, dan saya membukanya dengan tangan gemetar di toilet sekolah. Isinya selalu saja: Anda belum beruntung!
Maka saya segera memutar haluan. Energi dan waktu tidak ingin lagi disia-siakan untuk sesuatu yang tidak pasti. Saya kembali melanjutkan kebiasaan menulis artikel opini. Sejak duduk di bangku kelas 2 Aliyah/SMA artikel dan esai saya sudah dimuat di beberapa koran. Saya masih ingat honor pertama saya dikirimkan melalui pos wesel dan nyangkut di Balai Desa. Bapak Ketua RT di kampung saya, Haji Aman namanya, memberikannya kepada saya saat bertemu di mushalla sebelum salat magrib. Sambil menyerahkan itu, entah mengapa dia begitu iseng mengumumkan kepada para jamaah salat magrib jumlah yang tertera dalam wesel sebesar Rp7.500,00. Itu tahun 1986.
Ketika mulai duduk di bangku kuliah, tulisan-tulisan saya mengalir lebih deras. Bahkan saat duduk di semester empat, saya diberi kehormatan untuk mengisi kolom tetap di harian Jayakarta (kalau tidak salah diterbitkan oleh Kodam Jaya). Koran itu, seperti juga koran-koran lainnya hanya membuka rubrik budaya pada edisi minggu. Saya pun kerap membaca puisi-puisi dari para penyair yang tersebar di koran-koran edisi minggu itu. Tentu saja saya juga membaca majalah sastra seperti Horison. Jadi, walaupun tidak menulis puisi, diam-diam saya tetap menikmatinya.
Hampir semua puisi yang saya baca di media massa sebenarnya merupakan puisi yang sulit untuk dipahami. Saya sendiri menikmatinya bukan terutama karena saya dapat memahaminya, melainkan justru karena saya tidak memahaminya. Ada pola yang—entah dari mana dan sejak kapan—membentuk semacam kesadaran dalam diri saya bahwa semakin sulit sebuah puisi dipahami, semakin baik bagi saya. Semakin abstrak bahasanya semakin indah.
Membaca puisi ialah memasuki lorong-lorong gelap yang saya tidak tahu apakah di kiri-kanannya ada ranjau dan di ujung sana ada jurang. Tapi saya sudah terbiasa menikmati berada di dalam kegelapan itu. Sebuah puisi—seperti juga sebuah lukisan—yang mendorong lahirnya banyak penafsiran menunjukkan kekayaan makna puisi tersebut. Guru bahasa Indonesia saya di SMA dulu mengatakan bahwa puisi Chairil Anwar yang berjudul “Nisan” ditafsirkan berbeda-beda oleh para pengamat sastra asing. Begitu juga puisi pendek dari Sitor Situmorang berjudul Malam Lebaran, isinya hanya satu baris /”Bulan di atas kuburan”/ namun menimbulkan ragam penafsiran. Semakin banyak tafsir semakin baik, karena itu berarti puisi tersebut sangat kaya makna.
***
Belakangan saya tahu bahwa pola pikir semacam itu tidak bebas pengaruh. Ada semacam discourse dalam dunia perpuisian yang menghegemoni kesadaran publik bahwa yang disebut puisi ialah “ini”, bukan “itu”. Estetika puisi ialah “begini”, dan bukan “begitu”. Mungkin itu yang membuat puisi semakin rigid. Dunianya dikelilingi oleh tembok tinggi, di dalamnya hanya terdapat para penyair yang duduk satu meja dengan sesama penyair sambil minum anggur, mendiskusikan hal-hal penting tentang senja dan pohon cemara. Sementara itu—mengutip Chairil Anwar—“mereka yang bukan penyair tidak ambil bagian.”
Di tangan para penyairlah, hidup dan matinya puisi dipertaruhkan. Publik tidak ambil bagian karena mereka hanya konsumen—seperti umat dalam tradisi keagamaan yang harus ikut saja apa kata ulama. Hukum mana yang boleh diikuti dan tidak, sudah ada ketentuannya. Para penyair juga kerap diperlakukan seperti ulama yang kepada mereka dinisbatkan mana karya puisi dan mana yang bukan, mana sekte kepenyairan yang benar dan mana aliran sesat. Puisi-puisi jenis baru tidak tercipta karena seakan-akan ada paham bahwa “pintu ijtihad sudah ditutup”. Para penyair baru harus mengikuti saja salah satu mazhab yang sudah ada.
Jika benar begitu, maka inilah saat dimana dunia perpuisian sebenarnya justru membutuhkan lahirnya tradisi baru yang memberi nafas baru bagi dunia literasi. Sejarah kesusastraan di tanah air mencatat adanya dinamika pembaruan semacam itu, dan meletakkannya dalam arus perubahan budaya. Begitulah pergeseran dari Angkatan Balai Pustaka ke Pujangga Baru, kemudian Angkatan 1945, dan seterusnya. Karena itu, kelahiran tradisi baru dalam penulisan puisi sejatinya akan memulihkan fungsi pembaruan dalam kesusastraan.
Atas dasar itu, saya sangat terkesan bahwa seorang Sapardi Djoko Damono memberi apresiasi yang begitu besar terhadap puisi-puisi esai karya Denny JA dalam buku Atas Nama Cinta. Kita tahu bahwa Sapardi merupakan salah satu “paradigma” dalam dunia perpuisian modern di tanah air. Ia menjadi kiblat bagi banyak penyair muda. Karya-karyanya diakui telah menjelma menjadi kerajaan estetika tersendiri—estetika lirisisme, seperti yang mengemuka dalam diskusi “Imperium Puisi Liris” di Bentara Budaya Jakarta, Maret 2008. Sebagian karya puisi yang lahir dari tangan penyair-penyair muda, saya kira, juga bercorak sapardian.
Puisi-puisi esai karya Denny JA adalah kekecualian terhadap paradigma sapardian tersebut. Puisi sapardian bercorak liris, sementara puisi Denny JA bercorak esai—maka kemudian diberi nama “puisi esai”, sebuah gabungan istilah yang juga baru dalam kesusastraan Indonesia.
Kenyataan bahwa Sapardi memberi apresiasi dan dorongan bagi lahirnya karya-karya puisi jenis baru, memperlihatkan bahwa ia tidak ingin melihat puisi Indonesia terperangkap dalam statisme. Ada kerinduan terhadap terobosan, karena selama puluhan tahun penulisan puisi mengalami stagnasi, tidak ada perubahan yang berarti. Padahal, “pintu ijtihad” untuk menciptakan puisi-puisi jenis baru tidak pernah ditutup, dan mazhab-mazhab dalam sastra juga bermunculan, misalnya dulu ada mazhab sastra realisme sosial, mazhab sastra untuk sastra—yang merupakan derivasi dari ideologi seni untuk seni (l’art pour l’art), mazhab sastra kontekstual yang dipelopori oleh Ariel Heriyanto dan Arief Budiman, dan belakangan ada mazhab sastra dakwah.
***
Saya sendiri, pada mulanya, membaca puisi-puisi esai Denny JA dengan perasaan heran dan penuh tanya; ini puisi atau bukan? Kok penuturannya bercerita. Rupanya pengaruh paradigma lirisisme masih sangat kuat dalam kesadaran saya, sehingga nyaris kehilangan perspektif untuk menilai sebuah karya puisi yang bukan dari mazhab lirisisme.
Setelah berulang-ulang membacanya, saya meyakini puisi jenis ini sebenarnya yang biasa dibaca di panggung-panggung agustusan karena mudah dipahami. Saya menyebut panggung agustusan untuk menunjukkan bahwa popularitas sebuah puisi ialah ketika ia dibaca oleh masyarakat awam di atas panggung, dan agustusan adalah panggung yang paling populis.
Membaca puisi esai mengingatkan saya pada jenis tulisan opini. Di dalamnya ada gagasan yang tidak disembunyikan. Dituangkan dalam format puisi, namun cara bertuturnya esai. Yakni, dengan bahasa komunikasi sehari-hari. Bukankah puisi itu sendiri sebenarnya ialah komunikasi? Saya berpikir bahwa siapa saja bisa membuat puisi semacam ini—yang bukan penyair pun bisa ambil bagian!
Maka saya mulai menulis kembali puisi, setelah lebih dari dua puluh tahun tidak melakukannya. Melalui puisi esai, saya menemukan cara baru beropini. Dan inilah lima buah puisi esai saya yang dimuat dalam antologi ini, yang semuanya memotret dinamika kehidupan sosio-politik dan religius di tanah air beserta para aktornya.
***
Seperti halnya ritual-ritual dalam agama Islam yang saya peluk, dimana ada hukum yang fleksibel untuk mengikuti salah satu mazhab, maka pilihan saya untuk bermazhab pada puisi esai ini pun ada di dalam kerangka fleksibilitas tersebut. Sebagai penganut mazhab Syafii saya tidak menuduh sesat penganut mazhab Hanafi, Hanbali, Maliki, bahkan Dja’fari (Syiah). Sebagai penganut mazhab puisi esai, saya juga tidak hendak menisbikan mazhab puisi liris, puisi eMbeling, dan sebagainya. Bahkan saya tetap mengapresiasi, menikmati, dan seandainya mampu, mencipta puisi-puisi jenis itu.
Kiranya tidak perlu saya menjelaskan satu persatu dari lima puisi esai saya yang dimuat dalam buku ini. Saya serahkan kepada pembaca untuk menilainya. Sebagai mazhab baru dalam sastra Indonesia, puisi esai niscaya terus mencari bentuk melalui berbagai kreasi, walaupun mungkin tidak akan ada, dan memang tidak perlu ada, bentuk final dan standar. Puisi-puisi saya ini boleh jadi hanya salah satu varian saja dari apa yang dinamakan puisi esai itu.
Sebelum menutup pengantar ini, saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada banyak pihak yang memungkinkan terbitnya buku ini. Pertama-tama saya harus berterima kasih kepada Denny JA yang terus mendorong agar buku ini segera diterbitkan. Kritik, saran, dan masukan-masukannya telah menjadi bagian dari karya ini baik yang disampaikan melalui email maupun dalam berbagai pertemuan di Ciputat School—sebuah forum yang difasilitasi oleh Denny JA untuk menginspirasi pencerahan budaya.
Teman-teman lain di Ciputat School yang membaca naskah awal puisi-puisi ini juga ikut memberi masukan, bahkan kritik yang pedas, sehingga acapkali saya tidak bisa tidur nyenyak atas kritik-kritik tersebut. Namun saya tahu semuanya dilakukan dengan tulus demi kesempurnaan yang relatif. Para pegiat Ciputat School yang saya maksud ialah: Elza Peldi Taher, Jonminofri, Ihsan Ali Fauzi, Zuhairi Misrawi, Anick HT, Neng Dara Affiah, Novriantoni Kahar, Budhy Munawar-Rachman, Nur Iman Subono, Ali Munhanif, Jojo Rahardjo, dan lain-lain yang tidak cukup halaman untuk menyebutkannya satu persatu.
Teman-teman di Jurnal Sajak juga telah banyak memberi dukungan. Mereka adalah Agus R. Sarjono, Acep Zamzam Noor, Ahmad Syubbanuddin Alwy, Tugas Suprianto, dan khususnya Jamal D Rahman, yang bersedia meluangkan waktu menulis kata pengantar untuk buku ini.
Akhirnya, buku ini dipersembahkan kepada para bidadari yang selalu menyemarakkan hari-hari saya dengan canda dan tawa mereka: istri tercinta, Jumiatie Zaini dan anak-anak kami, Alifya Kemaya Sadra dan Raysa Falsafa Nahla, serta keponakan kami yang tinggal bersama kami, Winda Widyana.
Karya ini jelas sangat jauh dari sempurna untuk dipublikasikan. Namun saya berpegang pada satu adagium di dunia penulisan: Terbitkan karyamu hari ini, besok engkau buat yang lebih baik lagi! Selamat membaca.
Ciputat, 1 Juli 2012
Ahmad Gaus
_________________________________________________________________________________________________________
Buku KUTUNGGU KAMU DI CISADANE tersedia di gerai-gerai Gramedia. Anda juga bisa memesan melalui alamat2 di bawah ini:
FB: Gaus Ahmad
Twitter: @AhmadGaus
Email: gausaf@yahoo.com
PIN: 21907D51
_________________________________________________________________________________________________________