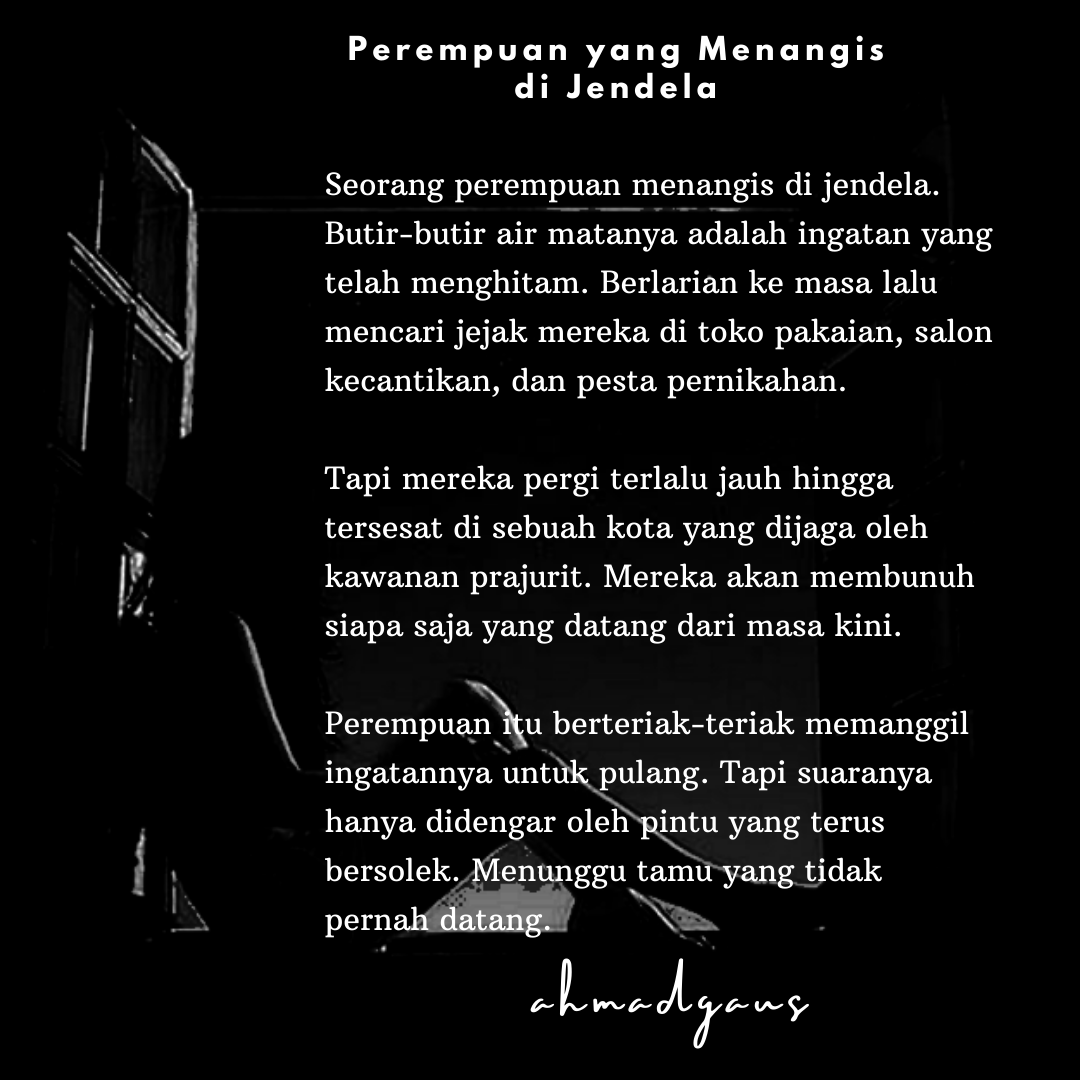Tag Archives: bahasa dan sastra indonesia
Hidup Terlalu Menarik untuk Dibenci

Nada Cinta

Perempuan yang Menangis di Jendela
Selamat Hari Puisi Sedunia
January Poem
KIDUNG CISADANE

Indahnya Cinta Segitiga
Dua orang perempuan saling menyayangi. Tapi, keduanya mencintai pria yang sama. Cinta segitiga terjalin begitu saja. Ada cemburu. Ada marah. Ada curiga. Tapi kasih sayang di antara kedua perempuan itu membuat mereka harus menafsirkan kembali cintanya pada si pria. Mereka tidak ingin kehilangan sahabat, tapi juga tidak mau ditinggal kekasih. Akhirnya sebuah kompromi dilakukan. Cinta segitiga terjalin mesra.
Masalah baru muncul ketika datang seseorang yang lain (pria atau wanita, hayoo tebak?). Cinta segitiga akhirnya berkembang menjadi persegi panjang. Romantis, seru, menggairahkan, penuh kelembutan, dan sekaligus brutal. Ikuti kisahnya dalam novel Hujan dalam Pelukan di platform NovelMe, selagi masih gratis, sebelum di-setting di halaman berbayar. Ini link-nya : https://share.novelme.id/starShare.html?novelId=22983
Mata yang Indah
“Aku ingin berjalan bersamamu
Dalam hujan dan malam gelap
Tapi aku tak bisa melihat matamu.”
(“Resah”, oleh Payung Teduh)
MATA YANG INDAH
Mata yang indah
adalah seribu kunang-kunang
yang berpindah dari lembah
ke taman pedestrian
dan membawaku kembali duduk
di sana — sudut kota yang memulakan segalanya dari keraguan.
Walau langit gelap
mata itu tetap purnama
tapi aku tak ingin menatapnya
karena aku akan tersiksa
maka kubiarkan kaki berjalan
dalam kegelapan.
Mata yang indah adalah muara
pelabuhan bagi biduk-biduk
resah dan kebahagiaan
dalam mata yang indah
kehidupan selalu basah
karena di kelopaknya yang rawan
hanya ada musim penghujan.
03/09/17
Rumah Budaya Nusantara
PUSPO BUDOYO, Tangsel.
Baca juga: [Puisi] Z
Masa Depan Bahasa dan Sastra Indonesia
Quote
“… selama ini ada kesenjangan antara bahasa baku dengan bahasa gaul. Pendulumnya bergerak terlalu ekstrem dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Harusnya kita punya bahasa “menengah” yang berfungsi sebagai bahasa pergaulan yang tidak terlalu kaku namun juga sekaligus memiliki karakter bahasa budaya tinggi.”
Ahmad Gaus yang bertindak sebagai pembicara utama berpendapat bahwa tidak ada perkembangan yang berarti dalam bahasa Indonesia sejak ia dibakukan, dipolakan dalam rumus bahasa yang baik dan benar. Yang terasa, ujarnya, justru kekakuan dalam berbahasa. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang sangat formal yang hanya cocok digunakan di forum-forum resmi. Di luar itu, seperti dalam pergaulan, bahasa yang baik dan benar itu tidak bisa digunakan, “Lucu sekali kalau kita bercakap-cakap dengan teman menggunakan bahasa baku,” tandasnya.
Dijelaskan bahwa selama ini ada kesenjangan antara bahasa baku dengan bahasa gaul. Pendulumnya bergerak terlalu ekstrem dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Harusnya kita punya bahasa “menengah” yang berfungsi sebagai bahasa pergaulan yang tidak terlalu kaku namun juga sekaligus memiliki karakter bahasa budaya tinggi.
Ia mencontohkan bahasa dalam film-film Indonesia yang tidak maksimal mengeksplorasi kekayaan estetik bahasa Indonesia. Akibatnya film-film kita gagal menyajikan sentuhan seni yang paripurna, sebab kita hanya disuguhi cerita. Berbeda dengan film-film produksi luar yang mampu mengintegrasikan kecanggihan cerita, sinematografi, dan sekaligus keindahan bahasa. “Kalau film hanya mampu menampilkan bahasa yang sama dengan bahasa sehari-hari, lalu di mana unsur seninya. Bahasa film harusnya setingkat atau beberapa tingkat lebih tinggi dari bahasa sehari-hari. Sebab salah satu fungsi film ialah mengedukasi, termasuk di dalamnya mengedukasi masyarakat agar memiliki selera bahasa yang berkelas.”
Tersingkirnya estetika dari bahasa Indonesia, menurut Gaus, disebabkan karena bahasa sudah dipisahkan dari sastra. Sehingga seperti jasad tanpa ruh, raga tanpa jiwa. Pendidikan sastra hanya menjadi bagian kecil dalam mata pelajaran bahasa. Ada komunitas sastrawan di satu pihak yang menjadi penguasa jagad sastra, di pihak lain ada masyarakat yang tidak mengenal sastra. Keduanya dipisahkan oleh tembok tinggi. Padahal di masa lalu masyarakat adalah pencipta karya sastra itu sendiri seperti yang terlihat dalam budaya berpantun. Saat ini pantun sudah hilang dari tradisi berbahasa, padahal anak-anak yang diajari pantun sejak dini akan tumbuh menjadi penutur bahasa yang baik.
Akibat lebih jauh dari terpisahnya bahasa dan sastra ialah, bahasa kita menjadi sangat kaku dan kering. Belum lagi orientasi politik bahasa yang cenderung pada birokrasi dan peraturan. “Masak cuma mau memasukkan 3 perubahan sepele saja harus mengeluarkan Peraturan Menteri yang mengubah EYD menjadi EBI. Ini menunjukkan rezim bahasa tidak mengerti persoalan dan minim wawasan,” tandas Gaus. Walhasil sejauh ini, bahasa Indonesia hanya dapat menjadi alat komunikasi dan tidak bisa menjadi ekspresi kebudayaan. Maka yang harus kita lakukan ialah memutus keterasingan masyarakat terhadap sastra. Bahasa butuh ruang untuk berkembang, dan salah satu medianya adalah karya sastra…”
Selengkapnya baca di sini: https://www.csrc.jalalon.com/news/diskusi-umum-masa-depan-bahasa-dan-sastra-indonesia-2
Aku Bertanya Pada Cinta

AKU BERTANYA PADA CINTA
Aku bertanya pada cinta
sampai kapan akan membiarkan rindu
terbelenggu dalam penjara jiwa.
Ia menggelengkan kepala
menitikkan airmata!
Aku bertanya pada rindu
sampai kapan akan membiarkan cinta
terpenjara dalam belenggu kalbu.
Ia menangis pilu
menumpahkan airmatanya di bahuku!
Akhirnya aku bertanya pada airmata
sudikah ia mempertemukan
cinta dan rindu di taman pelaminan
dimana tak ada lagi kesedihan.
Ia pergi meninggalkanku
sambil menangis tersedu-sedu!
— Gedung Film, Maret 2016
Baca juga: Mata yang Indah
Aku Tidak Memesan Malam

AKU TIDAK MEMESAN MALAM
puisi ahmad gaus
Aku tidak memesan malam
ia datang begitu saja
dituangkan angin ke cangkir kopi
“Untuk apa?” tanyaku
“Aduklah, lalu minum,” katanya, “sebentar lagi sepi akan datang
ia akan menemanimu mengobrol.”
Hei, siapa pula yang memesan sepi?
aku sedang ingin sendiri
seisi rumah sudah kukeluarkan
kuletakkan di pinggir jalan
pakaian yang kukenakan telah kulucuti
kusedekahkan pada pengemis yang nyaris telanjang
bahkan tangan, kaki, alat vital, mata, telinga, hidung
telah kuberikan pada orang-orang yang lewat
terserah mau mereka apakan
aku ingin menyendiri
benar-benar sendiri.
Dunia sekelilingku telah menjadi asing
orang-orang tak kukenal hilir mudik
menuju tempat-tempat hiburan
merayakan malam dengan tangisan yang meriah
sebagian lagi berjubel di pusat-pusat perbelanjaan
memasukkan sepi ke kantong-kantong plastik.
Biarlah aku tetap seperti ini
tanpa malam, tanpa sepi
sebab keduanya sama saja:
telah tercemar oleh bau busuk keramaian
hanya kesendirian yang membuatku nyaman
hidup apa adanya, penuh kepasrahan
seperti bayi yang baru dilahirkan
dan dibuang ke dalam selokan
lalu menyusu dari polutan.
Ciputat, 10/1/2016
Remy Sylado dan Gerakan Puisi Mbeling
Catatan Ahmad Gaus
Pada 12 Juli 2015 lalu budayawan dan sastrawan Remy Sylado genap berusia 70 tahun. Sejak remaja, pria kelahiran Makassar 12 Juli 1945 ini telah aktif menulis puisi, esai, cerpen, novel, drama, kolom, kritik, roman, juga buku-buku musikologi, dramaturgi, bahasa, dan teologi. Sebagai kado di hari ulang tahunnya, dan sekaligus doa untuk kesembuhannya (karena beliau sedang sakit), berikut saya turunkan sebuah catatan atas gerakan sastra yang pernah dipeloporinya pada tahun 1970-an: Gerakan Puisi Mbeling. Catatan ini semula merupakan makalah penulis yang disampaikan pada diskusi sastra di kampus Swiss German University (SGU) pada Mei 2013. Makalah ini pun pernah saya kirimkan kepada Bang Remy dengan harapan mendapat masukan-masukan dari beliau. Melalui emailnya pada 18 Juli 2013 ia menjawab: “Oke, sudah saya baca. Silahkan saja dilanjutkan.”
______________________________
Mei Hwa perawan 16 tahun
Farouk perjaka 16 tahun
Mei Hwa masuk kamar jam 24.00
Farouk masuk kamar jam 24.00
Mei Hwa buka blouse
Farouk buka hemd
Mei Hwa buka rok
Farouk buka celana
Mei hwa buka BH
Farouk buka singlet
Farouk buka celana dalam
Mei Hwa telanjang bulat
Farouk telanjang bulat
Mei Hwa pakai daster
Farouk pakai kamerjas
Mei Hwa naik ranjang
Farouk naik ranjang
Lantas mereka tidurlah
Mei Hwa di Taipeh
Farouk di Kairo
– Remy Sylado –
Apa saja bisa dan boleh ditulis menjadi puisi, dan siapa saja bisa dan boleh menjadi penyair. Begitulah kesan yang muncul dalam gerakan puisi mbeling yang dipelopori oleh Remy Sylado pada tahun 1970-an. Puisi berjudul Kesetiakawanan Asia Afrika yang dikutip di atas adalah salah satu contoh puisi mbeling yang dimuat di majalah Aktuil, tempat Remy berkiprah sebagai redaktur yang mengasuh rubrik yang juga diberi nama “Puisi Mbeling”. Belakangan puisi-puisi karya Remy Sylado selama 30 tahun diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia (2004) dalam buku berjudul Puisi Mbeling Remy Sylado.

Puisi mbeling lahir bersamaan dengan menguatnya konsolidasi politik pemerintah Orde Baru yang baru saja menaiki panggung kekuasaan. Euforia di kalangan politisi dan aktivis pergerakan yang telah berhasil menumbangkan rezim lama masih terasa. Berbagai harapan yang dipikulkan kepada pemerintahan baru kerapkali tidak menyisakan sikap kritisisme sebagaimana yang diperlihatkan pada era demonstrasi besar (1966). Alih-alih, justru yang muncul ialah usaha kolektif untuk menciptakan suasana kondusif dan “stabil”, bukan hanya dalam politik tapi juga sastra.

Sebagaimana dinyatakan oleh Remy Sylado, gerakan mbeling merupakan perlawanan yang diarahkan pada dua sasaran: pertama, estetika puisi yang tertawan dalam pikiran-pikiran konvensional yang melulu diungkap secara kabur dan gelap dalam bahasa berbunga-bunga sehingga puisi kehilangan tanggung jawabnya terhadap realitas, dan; kedua, situasi politik Orde Baru yang nyata dibingkai dalam gerontokrasi yang salah kaprah dengan slogan-slogan dari pejah gesang nderek bapak ke mikul dhuwur mendem jero.1)
Sebelum lahir sebagai genre puisi, gerakan mbeling sebenarnya telah muncul sebagai fenomena teater, dimana Remy Sylado melalui Dapur Teater 23761 di Bandung yang didirikannya mementaskan Genesis II, kemudian berturut-turut Exsodus II, dan Apocalypsis II. Dalam pentas-pentas teater itulah ia mengenalkan istilah mbeling. Anotasi II selalu disertakan sebagai lambang perlawanan terhadap yang sudah ada. Gerakan mbeling sebagai perlawanan budaya lewat teater juga diakui Remy sebagai reaksi terhadap WS Rendra dengan teaternya yang berpandangan bahwa perlawanan terhadap budaya mapan harus dilakukan dengan sikap urakan. Dalam Apologia Genesis II Remy menyatakan bahwa kata urakan dalam bahasa Jawa berkonotasi negatif: tidak sopan, tidak tahu aturan, dan kurang ajar. Karena itulah Remy, melalui teaternya, mengajukan kata “mbeling” yang lebih berkonotasi positif. Walaupun tetap bernuansa nakal, mbeling berasosiasi dengan pengertian pintar, mengerti sopan-santun, dan bertanggung jawab.
Gara-gara pementasan Genesis II itu Remy diinterogasi polisi Bandung selama hampir dua minggu. Namun peristiwa itu sekaligus mendorongnya untuk tetap menggunakan kata “mbeling” dan menjelaskan konsep di belakangnya sebagai budaya tandingan. Konsep itu kemudian ditransformasikan ke dunia puisi ketika pada tahun 1971 Remy bergabung dengan majalah Aktuil yang didirikan Denny Sabri, Toto Rahardjo, dan Sony Soeryatmadja. Kehadiran Remy di majalah hiburan dan musik yang berkantor di Jalan Lengkong Kecil 41, Bandung, itu menandai lahirnya gairah baru bersastra di kalangan remaja. Puisi yang semula dipandang sebagai benda pusaka yang sakral berubah menjadi barang biasa saja yang bisa ditulis oleh siapa saja. Melalui rubrik cerpen dan puisi mbeling yang diasuhnya, Remy mengajak kaum muda untuk bersastra.

Kesakralan puisi dan keangkeran majalah sastra menjadi alasan utama menjauhnya kaum muda dari budaya literasi yang sebenarnya berakar kuat di masyarakat. Kata-kata Chairil Anwar “yang bukan penyair tidak ambil bagian” justru menjadi pemicu untuk mengembalikan sastra (puisi) ke pangkuan khalayak. Gerakan puisi mbeling yang dipelopori Remy merupakan kritik terhadap fenomena onani dalam bersastra dimana para penyair menulis puisi untuk dibaca—karena hanya dipahami—oleh mereka sendiri. Gerakan ini diapresiasi oleh penyair Sapardi Djoko Damono sebagai “suatu usaha pembebasan”. Lebih lanjut Sapardi menulis:
Puisi rupanya telah menjadi bentuk sastra yang menarik minat orang-orang muda, terutama dalam masa perkembangannya sebagai sastrawan. Sajak-sajak yang dikirimkan ke majalah-majalah yang berprestasi tidak dapat segera dimuat… Sementara beberapa penyair mendapatkan tempat yang semakin kukuh dalam perkembangan puisi Indonesia, kaum muda yang baru mulai menulis itu merasakan semacam tekanan. Mereka merasa tidak bisa cepat tampil karena terhalang oleh tokoh-tokoh yang sudah ‘mapan’… Tambahan lagi kebanyakan mereka menetapkan kepenyairan berdasarkan dimuat atau tidaknya sajak-sajaknya dalam majalah sastra satu-satunya, Horison.2)
Sebagai gerakan perlawanan terhadap bahasa puisi yang berbunga-bunga namun gelap, puisi mbeling menawarkan konsep sebaliknya: puisi ditulis dengan bahasa biasa dan diusahakan terang-benderang. Dengan begitu, puisi bukan saja mudah dipahami sebagai pertanggungjawaban penyairnya terhadap realitas, namun ia juga membuka akses seluas-luasnya kepada siapa saja untuk menjadi penyair. Puisi tidak melulu harus berurusan dengan hal-hal yang agung dan mulia. Bisa saja ia menampilkan potret keseharian yang sepele. Simak, misalnya puisi berjudul “Sialan Banget” yang ditulis Remy Sylado: Sudah jatuh / dihimpit tangga // Hendak berdiri / digonggong anjing // Begitu lari terbirit / malah menginjak tahi.
Puisi itu menampilkan filosofi dari peribahasa yang sudah umum dikenal tentang situasi yang tidak menguntungkan. Namun oleh Remy, situasi itu diperburuk dengan menambahkan dua kesialan lainnya sehingga menimbulkan kesan tentang situasi yang benar-benar sial—sesuai dengan judulnya: Sialan Banget. Pilihan judul itu sendiri sudah keluar dari bahasa puisi yang “standar”. Sebagai sebuah eksperimentasi di tengah mainstream puisi serius yang mengusung narasi-narasi besar, puisi mbeling terbilang radikal dalam menjungkirbalikkan estetika perpuisian. Alih-alih, justru estetika itulah yang ingin dilawannya, antara lain dengan mensastrakan kosakata yang dianggap tabu untuk dimasukkan ke dalam puisi.

Memang tidak selamanya perlawanan terhadap ketabuan itu berjalan mulus. Salah satu puisi Remy yang dimuat di majalah Aktuil pernah membuat berang pemerintah. Saat itu Departemen Penerangan mengancam akan mencabut Surat Izin Terbit (SIT) majalah Aktuil. Hanya setelah para pengelola Aktuil membayar upeti—sesuai kelaziman pada saat itu—ancaman tersebut dibatalkan. Puisi yang menimbulkan masalah itu berjudul “Pesan seorang ibu kepada putranya”, terdiri dari tiga kata dalam tiga baris: jangan / bilang / kontol.3)
Puisi mbeling memang terkesan main-main. Tapi justru dengan cara itu Remy mengajak kaum muda untuk menulis. Dunia tulis-menulis, termasuk sastra, dikesankan sebagai dunia yang dekat dengan keseharian, tempat untuk bergurau dan menuangkan gagasan apa saja tanpa harus mengerutkan dahi terlalu lama. Dan usahanya itu mendapat respon meruah dari kalangan muda. Sejak rubrik puisi mbeling dibuka, sepuluh ribuan penulis dari seluruh wilayah Indonesia dan di manca negara telah mengirimkan karya mereka, dan ratusan di antaranya telah dimuat. Tentu saja pemuatan itu tidak asal-asalan melainkan melalui proses yang disesuaikan dengan kriteria dan idealitas yang dicanangkan oleh gerakan mbeling. Remy sendiri menyebut dirinya dalam proses itu sebagai despot yang di tangannya ada wewenang untuk mengubah dan mengedit naskah-naskah yang masuk ke redaksi.4)

Di bawah asuhan Remy Sylado sebagai penjaga gawang rubrik puisi mbeling majalah Aktuil, tercatat juga nama-nama — yang belakangan dikenal sebagai sastrawan — yang ikut menyemarakkan kegairahan berpuisi mbeling: Abdul Hadi WM, Seno Gumira Ajidarma, Noorca Massardi, Yudistira M. Massardi, Adhi M. Massardi, Mustofa Bisri (dengan nama samaran Mustov Abi Sri) dan nama-nama lainnya. Sampai sekarang corak kepenyairan mereka masih kental dengan nuansa mbeling dalam pengertian menyuarakan protes sosial dengan bahasa yang lugas dan terbuka.
Selain itu, pengaruh puisi mbeling juga melintasi majalah Aktuil. Ketika Remy Sylado berpindah ke majalah Top, ia tetap melanjutkan gerakan puisi mbeling dengan membuka rubrik bertajuk Puisi Lugu. Dari sini, sebagaimana dicatat oleh penyair Heru Emka, virus mbeling menyebar ke berbagai media massa: majalah Stop, Astaga, Sonata, Yunior, dan lain-lain. Berbagai surat kabar mingguan yang terbit di Jakarta maupun di daerah juga ikut tertular virus mbeling dengan membuka rubrik serupa. Begitu juga beberapa majalah remaja. Gerakan puisi mbeling telah menjadi gerakan menulis puisi alternatif yang memiliki spirit “yang bukan penyair boleh ambil bagian”. Dan, menurut Heru Emka lagi, gerakan ini telah mewarnai lembaran sejarah sastra Indonesia pada era awal tahun 1970-an.
Apakah itu artinya setelah era 1970-an gerakan ini meredup? Masa pasang naik dan surut sebetulnya lumrah dalam dunia apapun. Puisi mbeling sebagai gerakan perlawanan atau budaya tandingan sejak awal pasti telah menyadari dirinya adalah subkultur. Dan sebagai subkultur ia tidak akan menjadi arus utama (mainstream) yang langgeng. Namun, ia juga tidak akan mati sebab di setiap masa selalu ada proses pemapanan tradisi, dan di situlah yang mbeling akan hadir sebagai alternatif dan oposisi. Tegasnya, puisi mbeling mengabadikan dirinya di seberang aneka arus utama, dan menjadi kritikus yang nakal atas berbagai bentuk kemapanan, baik dalam sastra maupun politik.
Ketika belakangan Remy Sylado menerbitkan kumpulan puisinya setelah 30 tahun berlalu, tentu ia tidak bermaksud mengenang atau memperingati puisi mbeling yang pernah berjaya pada masanya. Buku ini berisi 143 puisi Remy Sylado yang ditulis antara 1971-2002.5) Penerbitan buku ini menjadi semacam reminder bahwa dalam lembaran sejarah sastra Indonesia pernah lahir gerakan puisi mbeling yang mengharu-biru dunia perpuisian. Dan penulisan puisi jenis itu hingga kini masih terus dilakukan. Bahkan, berdasarkan alasan yang telah dikemukakan di atas, puisi mbeling akan terus ditulis.
Buktinya, pada tahun 2012 lalu terbit sebuah buku berjudul Suara-Suara Yang Terpinggirkan, yang diberi judul kecil (tambahan): Antologi Puisi Mbeling.6) Sebagaimana mudah ditebak, kehadiran buku ini sontak menimbulkan spekulasi bahwa puisi mbeling bangkit lagi,7) karena dianggap telah lama menghilang dari peredaran. Buku ini memuat ratusan puisi dari para penyair yang dulu pernah terlibat dalam gerakan puisi mbeling: Yudhistira ANM Massardi, Adhie M Massardi, Noorca M Masardi, Darmanto Jatman, Nugroho Suksmanto, Satmoko Budi Santoso, Abdul Hadi WM, Gus Mustofa Bisri, Hendrawan Nadesul, F. Rahardi, Landung Simatupang, Jose Rizal Manua, Heru Emka (editor buku ini), dan lain-lain.
Buku ini diberi kata pengantar oleh Remy Sylado, Sang Bapak Puisi Mbeling itu sendiri. Bagaikan sebuah pernyataan sikap, tulisan kata pengantar Remy Sylado diberi judul Mbeling: Masih Berlanjut. Di sana ia menegaskan: “Bagi saya mbeling pernah ada, dan terserah, apakah mbeling masih akan ada. Sebab, pendirian saya sekarang: ada atau tiada tetap ada.” Selain menguraikan latar belakang estetik dan politik kelahiran puisi mbeling, dalam pengantarnya, Remy sebenarnya lebih banyak memanfaatkan kesempatan itu untuk meluruskan sejarah puisi mbeling. Mengapa diluruskan, karena menurutnya telah ada yang mengaku-ngaku sebagai pencetus puisi mbeling.8)
Menarik bahwa dalam buku ini dimuat banyak puisi yang berdata tanggal baru dari para penyair muda. Ini menunjukkan bahwa puisi mbeling memang masih menarik minat para penyair generasi baru dan karena itu terus diproduksi. Jangan kaget juga bahwa para penyair yang kini dikenal sebagai sastrawan kenamaan seperti Abdul Hadi WM, D. Zawawi Imron, Sutardji Calzoum Bachri, Gus Mustofa Bisri, Ahmadun Yosi Herfanda, Beni Setia, dan lain-lain, ternyata adalah para pendukung puisi mbeling yang produktif.
Gerakan mbeling yang semula digulirkan di panggung teater itu telah bermetamorfosis menjadi gerakan puisi yang menyebal dari arus utama untuk melawan tirani, menertawakan kebodohan, dan meludahi kemunafikan orang-orang dengan kedudukan terhormat. Dan selama fakta-fakta semacam itu berlintasan di depan wajah kita, maka selama itu pula puisi mbeling akan terus ditulis. Di bawah ini adalah puisi-puisi mbeling yang dikutip dari antologi Suara-suara Yang Terpinggirkan, yang ditulis oleh beberapa penyair generasi baru.
MBELING 2011
Sungguh
Susah
Terlambat
Empatpuluh
Tahun
Ide
Sudah
Keburu
Macet
(Pandu Ganesha)
KETIKA ADA BINTANG JATUH
TUHAN…..
Apa keinginanMU??
(Palestina Nabila)
BUNTU
mandek
Sudah lelah mataku, otakku, jariku,
cukup sekian dan terima kasih
(Palestina Nabila)
OTAK UDANG
banyak yang bilang
ada udang di balik batu
barangkali
si udang tengah mencari
otaknya yang hilang
(Rini Febriani Hauri)
JADI PRESIDEN
Seandainya aku jadi presiden
Semua orang tak usah kerja
Uang kita cetak saja
Bagikan setiap hari
Petani tak usah ke sawah
Libur tiap hari
Sekolah juga tutup saja
Gurunya tak mau kerja
Orang sakit mati saja
Dokternya juga tak mau praktek lagi
Kita makan uang saja
Karena tak ada yang bisa dibeli
Makanya jangan pilih aku jadi presiden..
(Ren Ren Gumanti)
Karakter dari puisi-puisi di atas masih senada dengan puisi-puisi mbeling yang ditulis oleh Remy Sylado 40 tahun silam: terkesan lugu, semaunya, tidak peduli dengan kata-kata indah, melawan logika umum. Pendeknya, menyimpang dari penulisan puisi yang standar. Ya, begitulah. Namanya juga puisi mbeling. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Remy sendiri, tidak semua tulisan berbentuk puisi yang dibuat main-main dan menekankan sifat-sifat pop adalah otomatis puisi mbeling.
Karena lahir dalam konteks perlawanan terhadap estetika puisi yang tertawan oleh pikiran konvensional dan counter culture terhadap kemunafikan politik yang muncul dalam bahasa-bahasa feodal, maka puisi mbeling membawa kredo tersendiri: pertanggungjawaban sastra terhadap realitas baik-buruk. Puisi yang main-main, menurut Remy, justru adalah puisi yang dibingkai dengan bahasa indah namun hanya bisa dinikmati sendiri oleh penulisnya. Padahal puisi akan dibaca oleh khalayak.
Lebih jauh Remy Sylado bahkan berpandangan bahwa di dalam puisi ada pesan-pesan kenabian dan relijiositas. “Puisi seyogianya mengandung nilai-nilai kawruh seperti yang terdapat dalam akar budaya Jawa,” ungkap Remy, yang memperoleh Khatulistiwa Literary Award tahun 2002 melalui novel Kerudung Merah Kirmizi, dan Anugrah Sastra 2011 dari Komunitas Nobel Indonesia.[]
Biodata Remy Sylado:
REMY SYLADO lahir di Makassar 12 Juli 1945. Dia salah satu sastrawan Indonesia. Nama sebenarnya adalah Yapi Panda Abdiel Tambayong (Jampi Tambajong). Ia menghabiskan masa kecil dan remaja di Solo dan Semarang. Sejak usia 18 tahun dia sudah menulis kritik, puisi, cerpen, novel, drama, kolom, esai, sajak, roman popular, juga buku-buku musikologi, dramaturgi, bahasa, dan teologi.Ia memiliki sejumlah nama samaran seperti Dova Zila, Alif Dana Munsyi, Juliana C. Panda, Jubal Anak Perang Imanuel. Dibalik kegiatannya dibidang musik, seni rupa, teater, dan film, dia juga menguasai sejumlah bahasa.
Remy Sylado memulai karir sebagai wartawan majalah Tempo (Semarang, 1965), redaktur majalah Aktuil Bandung (1970), dosen Akademi Sinematografi Bandung (1971), ketua Teater Yayasan Pusat Kebudayaan Bandung. Remy terkenal karena sikap beraninya menghadapi pandangan umum melalui pertunjukan-pertunjukan drama yang dipimpinnya.
Selain menulis banyak novel, ia juga dikenal piawai melukis, dan tahu banyak akan dunia perfilman. Saat ini ia bermukim di Bandung. Remy pernah dianugerahi hadiah Sastra Khatulistiwa 2002 untuk novelnya Kerudung Merah Kirmizi.
Dalam karya fisiknya, sastrawan ini suka mengenalkan kata-kata Indonesia lama yang sudah jarang dipakai. Hal ini membuat karya sastranya unik dan istimewa, selain kualitas tulisannya yang sudah tidak diragukan lagi. Penulisan novelnya didukung dengan riset yang tidak tanggung-tanggung. Seniman ini rajin ke Perpustakaan Nasional untuk membongkar arsip tua, dan menelusuri pasar buku tua. Pengarang yang masih menulis karyanya dengan mesin ketik ini juga banyak melahirkan karya berlatar budaya diluar budayanya. Diluar kegiatan penulisan kreatif, ia juga kerap diundang berceramah teologi.
Karya yang pernah dihasilkan olehnya antara lain : Orexas, Gali Lobang Gila Lobang, Siau Ling, Kerudung Merah Kirmizi (2002). Kembang Jepun (2003), Matahari Melbourne, Sam Po Kong (2004), Rumahku di Atas Bukit, 9 dari 10 Kata Bahasa Indonesia adalah Bahasa Asing, dan Drama Musikalisasi Tarragon “ Born To Win “, dan lain-lain.
Remy Sylado pernah dan masih mengajar di beberapa perguruan di Bandung dan Jakarta seperti Akademi Sinematografi, Institut Teater dan Film, dan Sekolah Tinggi Teologi. (Dikutip dari http://www.goodreads.com/author/show/541628.Remy_Sylado)
Catatan Kaki
- Remy Sylado, “Kata Pengantar”, dalam Heru Emka, ed., Suara-suara yang Terpinggirkan (Semarang: Kelompok Studi Sastra Bianglala, Mei 2012), hal. xv
- Sapardi Djoko Damono, Kesusastraan Indonesia Modern: Beberapa Catatan (Jakarta, Gramedia, 1983), hal. 90
- Remy Sylado, “Kata Pengantar”, dalam Heru Emka, ibid.
- Ibid.
- Remy Sylado, Puisi Mbeling (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2004)
- Heru Emka, ed., Suara-suara yang Terpinggirkan (Semarang: Kelompok Studi Sastra Bianglala, Mei 2012).
- “Puisi mbeling bangkit lagi!” Begitu statemen pembukaan artikel berjudul “Mbeling” dalam Puisi “Urakan” yang ditulis Riza Multazam Luthfy sebagai ulasan buku Suara-Suara Yang Terpinggirkan, dalam Koran Jakarta, 1 Oktober 2012.
- Dalam hal ini Remy menyebut nama Jeihan. “Untuk banyak hal Jeihan adalah kawan akrab, tetapi untuk satu hal menyangkut mengaku-akunya sebagai pencetus puisi mbeling, saya tidak menghargainya,” tulis Remy dalam “Kata Pengantar”, ibid., hal. xix). Ia juga mengeritik penyair Soni Farid Maulana dan pengamat sastra Jakob Sumardjo yang menurutnya telah percaya begitu saja pada Jeihan. Keduanya masing-masing menulis prolog dan epilog untuk buku berjudul Mata mBeling Jeihan (Jakarta: Grasindo, 2000).
____________________________________________________
PARADE PEMBACAAN PUISI oleh Ahmad Gaus



Follow my IG @gauspoem